OPINI - Pasar tradisional sedang berdiri di persimpangan (zaman) digital. Di satu sisi, ia menyimpan sejarah panjang interaksi ekonomi rakyat: ruang bertemunya produsen dan konsumen kecil, tempat transaksi dilakukan dengan bahasa, senyuman, dan saling percaya. Di sisi lain, revolusi digital menggulung cepat, membawa pola konsumsi baru yang serba instan dan minim interaksi manusia.
Ketika 'marketplace' menawarkan layanan cepat antar sampai rumah, dan toko swalayan buka 24 jam dengan suhu dingin dan rak simetris, posisi pasar rakyat kian terjepit. Yang menjadi soal: akankah pasar rakyat hanya menjadi artefak ekonomi masa lalu, atau justru menjelma menjadi simpul ekonomi dan budaya masa depan?
Lebih dari Sekadar Tempat Jual Beli
Pasar tradisional bukan sekadar lokasi jual-beli kebutuhan pokok. Ia adalah ekosistem sosial dan budaya. Di sana ada kehidupan: negosiasi yang penuh canda, sapa pelanggan yang akrab, hingga hubungan emosional yang tak bisa dibangun oleh algoritma e-commerce.
Bahkan lebih dari itu, pasar tradisional juga menyimpan kekayaan produk yang sulit ditiru oleh 'marketplace' modern. Kebutuhan sehari-hari seperti sayur segar, buah musiman, bumbu dapur, daging potong, ikan laut, hingga palawija lokal masih lebih hidup di pasar rakyat. Kesegaran, keberagaman, dan fleksibilitas dalam jumlah pembelian adalah nilai tambah yang tidak bisa di-klik dalam keranjang belanja digital.
Sayangnya, keunggulan ini masih belum cukup jika tidak dibarengi dengan inovasi layanan. Banyak pasar masih bergulat dengan persoalan klasik: fasilitas buruk, kebersihan minim, dan pengelolaan yang semrawut. Di saat yang sama, para pedagang banyak yang belum mampu menyesuaikan diri dengan era digital dan perubahan selera konsumen muda.
Transformasi yang Tak Terhindarkan
Pasar tradisional harus berubah—bukan menjadi tiruan pasar modern, tetapi menjadi dirinya sendiri yang lebih kuat dan relevan. Setidaknya, Ada lima langkah kunci yang bisa menjadi arah transformasi.
Pertama, kualitas layanan harus ditingkatkan. Penataan kios, kebersihan, dan kenyamanan menjadi fondasi. Bukan hanya agar pembeli betah, tapi juga agar pasar dapat kembali menjadi tempat bertemu dan bersilaturahmi. Di banyak daerah, pasar adalah tempat berkumpul keluarga besar: bertemu sanak saudara, menanyakan kabar tetangga lama. Sentuhan kekeluargaan ini adalah kekayaan sosial yang tidak bisa dibeli dari 'keranjang daring'.
Kedua, penguatan identitas produk lokal. Pasar tradisional harus berani menonjolkan produk unggulan yang tidak tersedia di retail modern. Kesegaran, cita rasa khas daerah, hingga variasi olahan rumah tangga bisa menjadi kekuatan diferensiasi yang besar. Namun produk-produk ini perlu dikemas lebih menarik, diberi cerita, diberi nilai. Di sinilah pentingnya branding kolektif pasar, bukan hanya sekadar jualan kiloan.
Ketiga, pelayanan harus melampaui ekspektasi. Pasar bisa membuka jasa antar pesanan untuk warga sekitar melalui layanan berbasis WhatsApp atau platform lokal. Di sinilah justru keunggulan pasar rakyat: pendekatan personal, tahu selera langganan, tahu siapa yang tidak makan pedas, siapa yang selalu beli sebelum subuh. Ini adalah bentuk layanan yang tak bisa dikustomisasi oleh AI.
Keempat, menjadikan pasar sebagai ruang hidup dan kreatif. Banyak pasar di kota-kota besar mulai membuka 'foodcourt' dengan konsep terbuka, tempat duduk nyaman, dan sajian kuliner lokal yang autentik. Pasar bukan sekadar tempat belanja, tapi tempat nongkrong, tempat bertemu komunitas, tempat mencari inspirasi. Anak-anak muda dan komunitas kreatif harus diberi ruang: untuk mural di dinding atau jalan pasar, untuk pentas musik akhir pekan, atau untuk bazar kreatif bulanan.
Kelima, penguatan kehadiran digital. Pasar bisa menyediakan sistem pre-order harian, katalog digital produk segar, hingga integrasi dengan layanan pengiriman lokal. Hal ini bukan untuk menggantikan pengalaman berbelanja langsung, tapi memperluas akses bagi mereka yang tidak sempat datang. Bahkan, inovasi semacam layanan “pasar keliling digital” bisa dikembangkan: satu aplikasi, satu koordinator, dan seluruh pedagang terlibat dalam sistem distribusi berbasis lingkungan.
Peran Daerah dan Dukungan Serius
Namun, inovasi saja tak cukup jika negara hanya menjadi penonton. Pemerintah, terutama daerah, perlu tampil sebagai fasilitator aktif. Bukan hanya memperbaiki infrastruktur pasar secara fisik, tetapi juga membangun ekosistem digital dan sosial yang menopang keberlangsungan pasar tradisional.
DAK Tematik bisa diupayakan dan diarahkan untuk revitalisasi pasar berbasis inovasi dan komunitas. Program pelatihan literasi digital, pendampingan pemasaran, hingga pembentukan platform e-commerce lokal untuk pasar tradisional bisa menjadi program prioritas. Pemerintah juga bisa menyediakan subsidi perangkat digital dan insentif bagi pedagang yang berani bertransformasi. Regulasi zonasi juga penting. Pasar modern tidak bisa dibebaskan tumbuh tanpa kendali. Persaingan yang sehat harus dilindungi oleh negara. Perlindungan terhadap pasar rakyat bukan bentuk proteksi sempit, tapi keberpihakan pada keadilan ekonomi.
Ruang Inspirasi dan Harapan
Beberapa contoh pasar yang sukses melakukan transformasi sudah ada. Pasar Badung di Denpasar tampil modern dengan sentuhan lokal dan sistem digital pembayaran. Pasar Santa di Jakarta menjadi ruang kolaborasi anak muda. Di berbagai kota, muncul gerakan pedagang muda yang mem-branding dagangan mereka dengan pendekatan visual dan 'storytelling' yang kuat.
Model seperti ini perlu disebarluaskan dan direplikasi dengan penyesuaian lokal. Bahkan bisa dikembangkan program inkubasi bisnis di pasar: di mana pedagang muda dilatih mengelola bisnis, diajari cara membuat konten produk, hingga mengembangkan strategi penjualan daring.
Penutup
Pasar tradisional bukanlah entitas purba yang tak mampu bersaing. Ia hanya butuh dipoles, dibela, dan diberi ruang untuk berkembang. Di era disrupsi ini, bertahan saja tidak cukup. Pasar tradisional harus bergerak: merangkul teknologi tanpa kehilangan jiwanya. Jika itu bisa dilakukan, pasar bukan hanya akan tetap hidup—ia akan kembali menjadi pusat kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya yang berdenyut dari jantung masyarakat.
Oleh: Indra Gusnady, SE, MM (Pengamat Kebijakan Publik & Perencanaan Kota / Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok)





























:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4863706/original/094546500_1718355381-Kolase_-_Aksi_PertandinganTimnas_Indonesia_di_Kualifikasi_Piala_Dunia_Berbagai_Edisi_copy.jpg)





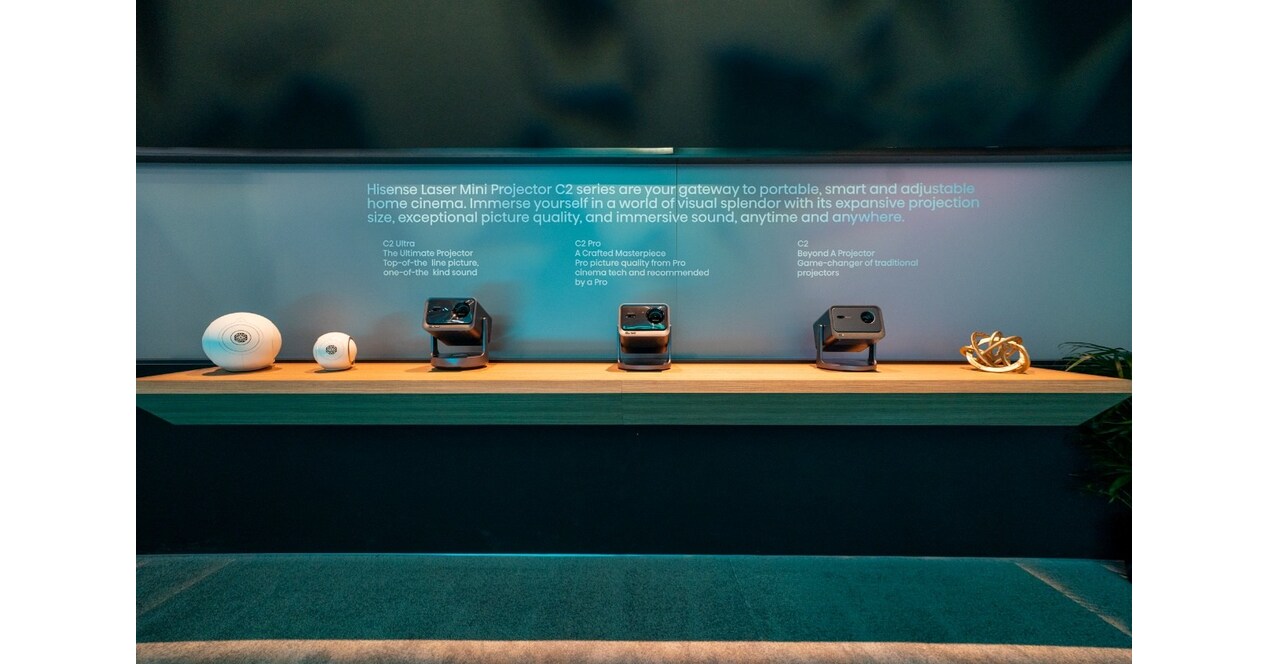



:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4884798/original/003422400_1723029847-BRI_LIGA_1_-_Ilustrasi_Logo_Klub_BRI_Liga_1_Musim_2024_2025_copy.jpg)





