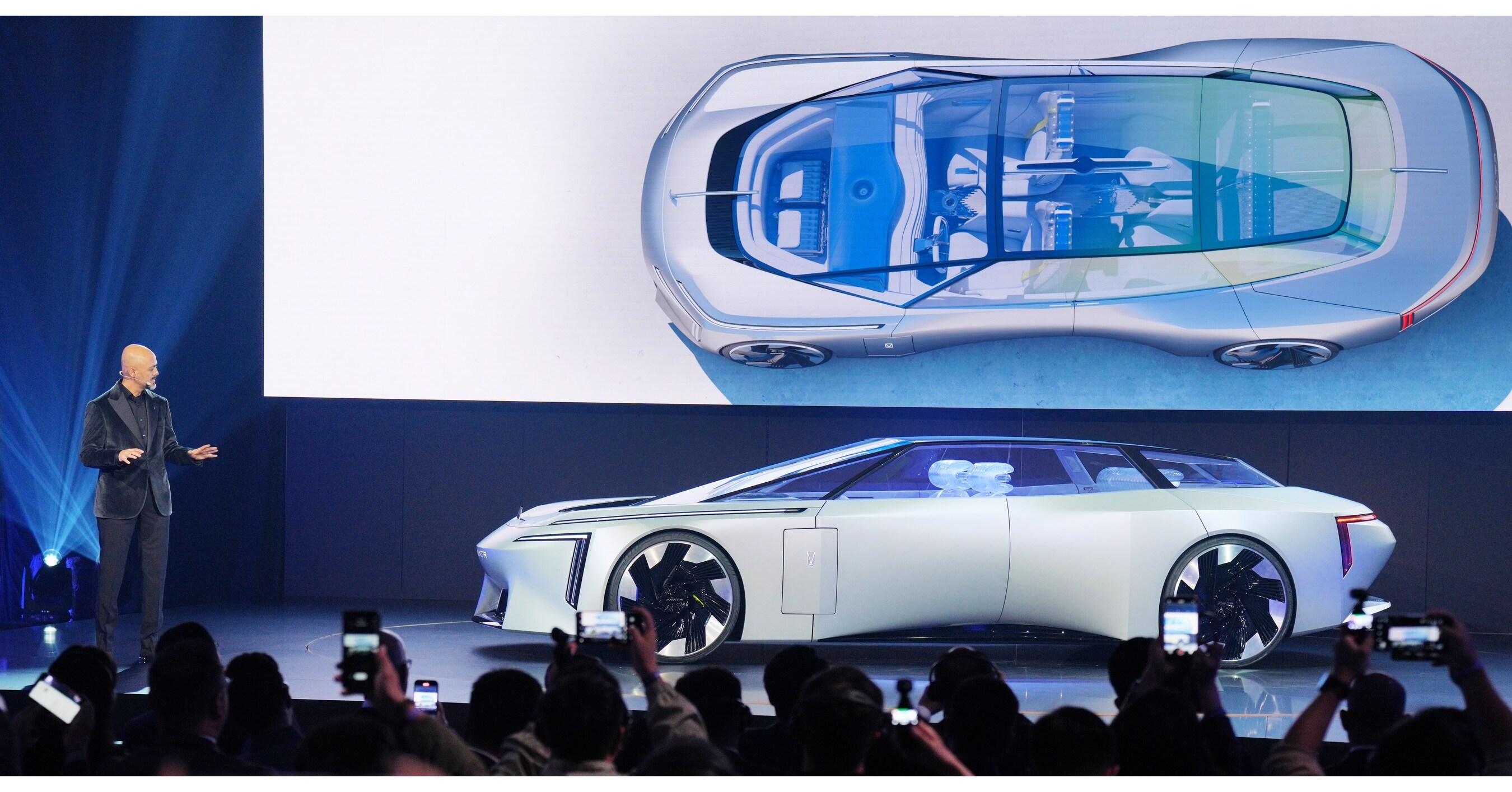OPINI - Menteri Keuangan Sri Mulyani kerap menenangkan publik dengan kalimat singkat: “Utang kita produktif.” Kata-kata itu seolah menjadi mantra setiap kali menjawab pertanyaan soal beban utang negara yang terus meningkat. Jalan tol, bandara, bendungan, dan infrastruktur lain menjadi bukti visual yang dikedepankan.
Namun, apakah benar utang yang ditarik selama era pemerintahan Joko Widodo produktif?
Ekonom Prof. Awalil Rizki mencoba menguji klaim itu dengan data. Ia menyoroti tiga ukuran utama: tambahan aset, peningkatan pendapatan negara, dan pertumbuhan ekonomi. Hasilnya justru menunjukkan sebaliknya.
Pertama, dari sisi aset. Idealnya, utang menambah kepemilikan aset tetap negara. Namun laporan keuangan pemerintah justru memperlihatkan nilai aset yang stagnan, bahkan menurun karena penyusutan. Kenaikan nilai aset lebih banyak berasal dari revaluasi akuntansi pada 2015 serta 2017–2019, bukan pembelian baru yang dibiayai utang. Infrastruktur memang bertambah, tetapi nilainya tidak sebanding dengan laju utang yang ditarik.
Kedua, dari sisi pendapatan. Rasio Total utang terhadap penerimaan negara membengkak dari sekitar 168 persen pada awal Jokowi menjadi hampir 300 persen pada 2024. Artinya, utang tumbuh jauh lebih cepat daripada kemampuan negara mengumpulkan pajak dan pendapatan lain. Jika tren ini berlanjut, ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan rakyat akan makin sempit.
Ketiga, dari sisi pertumbuhan ekonomi. Utang produktif seharusnya mendorong pertumbuhan lebih tinggi dari laju penambahannya. Faktanya, ekonomi Indonesia rata-rata hanya tumbuh 5 persen per tahun, sementara utang konsisten naik lebih tinggi. Bahkan di 2023, tahun terbaik sekalipun, utang tumbuh 5, 29 persen sedangkan ekonomi hanya 5 persen. Produktivitas yang dijanjikan tetap tak muncul.
Di balik perdebatan ini, ada soal transparansi. Sri Mulyani sering menyebut angka utang sekitar Rp8.000 triliun. Padahal, jika menghitung seluruh kewajiban yang tercatat dalam laporan keuangan negara, jumlahnya sudah menembus Rp12.657 triliun. Sri Mulyani mungkin tidak berbohong secara langsung, tetapi cara menyajikan data jelas tidak menggambarkan realitas sepenuhnya.
Masalahnya, evaluasi serius soal produktivitas utang hampir tak pernah dilakukan. DPR jarang menuntut penjelasan, sementara publik terbuai oleh simbol-simbol fisik infrastruktur. Kritik ekonom lebih sering dianggap perdebatan teknis, padahal yang dipertaruhkan adalah kesehatan fiskal jangka panjang.
Kini, ketika cicilan pokok dan bunga semakin besar, pertanyaan publik makin relevan: sampai kapan utang terus ditambah tanpa hasil nyata yang bisa menyehatkan ekonomi?
Ekonomi sejatinya bukan diukur dari seberapa banyak jalan tol berdiri, melainkan seberapa besar ia menambah lapangan kerja, memperkuat daya beli rakyat, dan meningkatkan pendapatan negara. Tanpa tiga ukuran itu, utang hanya akan menjadi beban yang diwariskan ke generasi berikutnya.
Kita memerlukan narasi baru: bukan sekadar utang produktif, tetapi utang yang benar-benar terukur manfaatnya. Jika serius, seharusnya ada laporan rutin tentang seberapa besar dampak utang terhadap aset, pendapatan, dan pertumbuhan. Tanpa itu, jargon produktif hanyalah iklan politik, bukan kenyataan.
Oleh: Indra Gusnady