Bukittinggi-Di sebuah rumah kontrakan kecil yang mulai usang, tinggal seorang ibu bernama Bu Lastri bersama anak bungsunya, Dani. Suaminya telah lama tiada, meninggalkan ruang kosong yang tak pernah benar-benar bisa diisi. Sejak itu, Bu Lastri menjalani hari-hari dalam perjuangan dan kesabaran.
Anak sulungnya, Dinda, kini tinggal di Jakarta bersama suaminya. Sejak menikah, Dinda jarang pulang. Katanya sibuk, katanya hidup di kota penuh tekanan. Tapi Bu Lastri hanya ingin tahu kabarnya, hanya ingin mendengar suaranya, atau sekadar tahu bahwa putrinya masih mengingat ibu yang dulu menggendongnya dalam hujan dan memeluknya saat demam tinggi.
Dani, si bungsu, memang tinggal bersamanya. Tapi sebagai anak muda yang sedang tumbuh, pikirannya masih terbang ke banyak arah. Dunia luar lebih menarik dari rumah yang selalu penuh kekhawatiran soal uang, listrik, dan kebutuhan dapur. Ia sering pulang larut, atau kadang hanya diam dalam kamar.
Setiap pagi, Bu Lastri menyapu halaman kecil. Lalu ia mulai menjahit—pekerjaan sampingan yang memberinya harapan. Ia tak banyak bicara, tapi pikirannya penuh. Tentang bagaimana membayar kontrakan bulan depan. Tentang harga beras yang naik. Tentang cucu yang belum pernah ia peluk.
Pernah suatu malam, hujan turun deras. Bocor atap menetes deras di ruang tamu. Dani belum pulang. Bu Lastri duduk di kursi rotan, menatap layar ponsel yang kosong. Ia membuka galeri, melihat foto pernikahan Dinda. Senyum anaknya begitu cantik, begitu bahagia. Tapi di situ tak ada dirinya.
Air matanya menetes. Bukan karena kesedihan semata, tapi karena rindu yang tak terucap. Ia ingin Dinda pulang. Bukan untuk membawa uang atau oleh-oleh, hanya untuk memeluk ibunya. Menyentuh tangannya yang kasar karena bertahun-tahun bekerja sendiri.
“Ibu baik-baik saja, Dinda, ” gumamnya lirih, seolah mengirimkan pesan lewat angin.
Namun yang datang hanya sunyi.
Dan di tengah semua itu, Bu Lastri tetap berdiri. Tubuhnya mulai renta, tapi hatinya tetap kuat. Ia tak pernah meminta banyak. Hanya sedikit perhatian. Sedikit waktu. Sedikit cinta yang dulu begitu sering ia berikan tanpa hitungan.
Karena seorang ibu, meski ditinggalkan, meski tak diingat, tetap mencintai. Ia bertahan, meski badai tak kunjung reda.
(Lindafang)




























:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4863706/original/094546500_1718355381-Kolase_-_Aksi_PertandinganTimnas_Indonesia_di_Kualifikasi_Piala_Dunia_Berbagai_Edisi_copy.jpg)




:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4884798/original/003422400_1723029847-BRI_LIGA_1_-_Ilustrasi_Logo_Klub_BRI_Liga_1_Musim_2024_2025_copy.jpg)








:strip_icc():format(webp):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/bola/watermark-color-landscape-new.png,598,20,0)/kly-media-production/medias/5048156/original/007018500_1734015846-20241212AA_Asean_Cup_2024_Indonesia_vs_Laos-22.JPG)
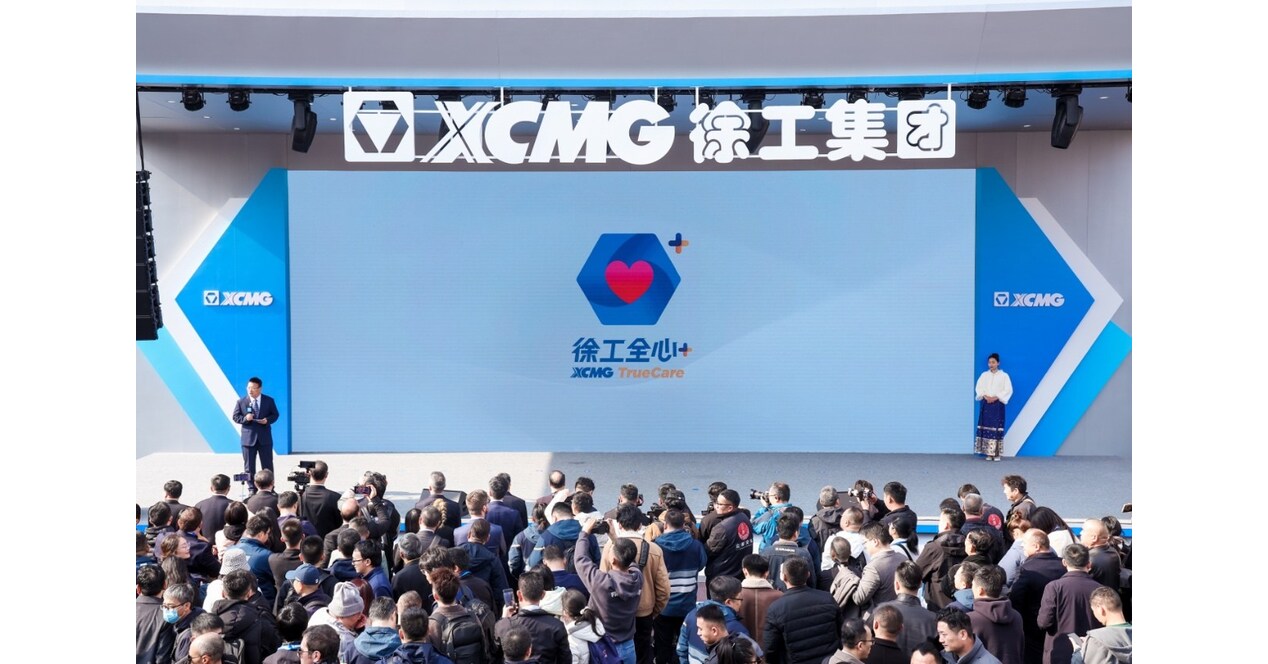
:strip_icc():format(webp):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/bola/watermark-color-landscape-new.png,598,20,0)/kly-media-production/medias/5070563/original/091928300_1735486103-083A8504.jpg)
