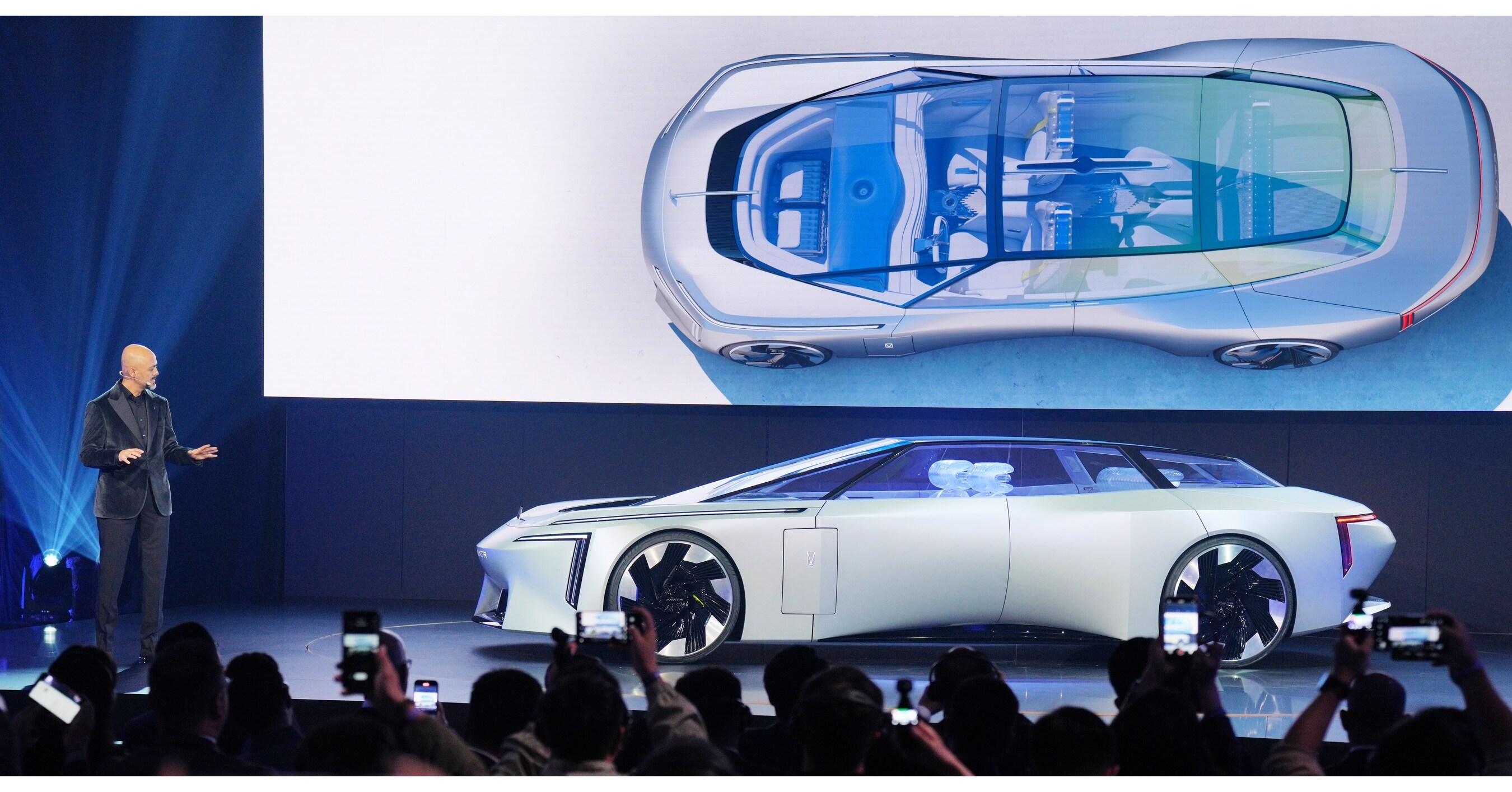SURABAYA - Pernyataan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi, Prof. Brian Yuliarto, saat memberikan kuliah di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) beberapa waktu lalu, bagaikan lentera yang menerangi arah baru dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Beliau tak segan menyentil akar masalah yang menghambat kemajuan kampus dan bangsa.
“Di negara dengan ekonomi bagus, selalu ada industri kuat. Di belakang industri kuat, selalu ada kampus hebat, ” ujar Prof. Brian Yuliarto. Kalimat ini bukan sekadar retorika, melainkan sebuah cermin yang memaksa kita merenungi sejauh mana ambisi kita sebagai bangsa untuk meraih kehebatan.
Sindiran tajam dilontarkan Prof. Brian Yuliarto terhadap fenomena yang ia sebut sebagai mentalitas “Jam Lima Sore”. “Bagaimana mau mengejar target itu, jika mentalitas kita masih sebatas mentalitas jam lima sore?” tanyanya retoris. Ini adalah diagnosis mendalam atas penyakit kronis yang menggerogoti semangat akademik dan intelektual kita.
Beliau membandingkan dengan Korea Selatan, di mana mahasiswa rela bergelut di laboratorium hingga larut malam, bahkan pukul sembilan malam, untuk memperdebatkan temuan-temuan baru. Kontras dengan realitas di Indonesia, di mana banyak anak muda, bahkan mahasiswa, justru larut dalam zona nyaman: asyik menggulir layar gawai, tenggelam dalam permainan daring, atau terpaku di depan layar televisi.
“Ini bukan soal menyalahkan hiburan. Hiburan adalah hak setiap individu. Namun, ini soal urgensi. Soal kegilaan untuk maju, ” tegas Prof. Brian. Beliau menekankan bahwa bangsa yang besar hanya bisa ditopang oleh kaum elite yang memiliki ambisi membara dan etos kerja tinggi. Kaum elite ini, tambahnya, adalah mahasiswa, dosen, dan guru besar—motor penggerak inovasi, pendorong roda industri, dan penentu arah masa depan bangsa.
Namun, realitas dunia kampus saat ini seringkali terjebak dalam paradigma lama. Dosen sibuk mengejar jumlah publikasi di jurnal internasional terindeks Scopus, menghasilkan tumpukan penelitian yang lebih banyak menjadi dokumen tak tersentuh di perpustakaan. Sementara itu, sebagian besar mahasiswa memandang kuliah hanya sebagai formalitas untuk meraih gelar, bukan sebagai ladang untuk mengasah ambisi dan kreativitas.
Fenomena ini, menurut Prof. Brian, adalah manifestasi dari mentalitas “jam lima sore”: bekerja seadanya, pulang tepat waktu, dan sebisa mungkin menghindari tantangan besar.
Untuk mengatasi ini, Prof. Brian Yuliarto mengusulkan sebuah redefinisi peran dosen. Dosen tak lagi hanya dilihat sebagai akademisi yang diukur dari jumlah publikasi, melainkan sebagai inovator yang mampu menghasilkan royalti dari penelitiannya. Ini adalah pergeseran paradigma yang radikal, di mana penelitian harus lebih “membumi”, relevan dengan kebutuhan industri, mampu menjawab permasalahan publik, dan menghasilkan dampak ekonomi yang nyata.
“Ketika riset laku, dosen dan kampus mendapat pemasukan, industri mendapat solusi, dan negara melaju menuju kemajuan. Ini adalah simbiosis mutualisme yang ideal, ” paparnya. Namun, Prof. Brian menyadari bahwa pencapaian ini tidaklah mudah dan dosen tidak bisa bekerja sendirian.
Di sinilah peran strategis Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Pusat Penelitian menjadi krusial. Prof. Brian berpendapat, kantor mereka seharusnya tidak hanya berada di dalam kampus, melainkan harus merambah ke luar: di kawasan industri, di ruang rapat Kamar Dagang dan Industri (Kadin), bahkan di lobi kementerian.
“Mereka adalah duta besar kampus, yang bertugas menjemput peluang, menciptakan kolaborasi, dan memasarkan produk riset ke dunia nyata, ” jelasnya. Pandangan ini pun sejalan dengan pemikiran Prof. Michael Porter, pakar strategi bisnis dari Harvard, yang menekankan pentingnya klaster inovasi—kolaborasi erat antara universitas, industri, dan pemerintah—sebagaimana tertuang dalam bukunya *Competitive Advantage of Nations* (1990).
Contoh nyata dapat dilihat di Korea Selatan, di mana universitas-universitas ternama seperti KAIST dan Seoul National University menjalin kerja sama erat dengan raksasa industri seperti Samsung dan Hyundai, menciptakan ekosistem inovasi yang kokoh dan mendorong ekonomi nasional. Di Indonesia, kolaborasi semacam ini masih sporadis, kerap terhambat oleh birokrasi yang berbelit, kurangnya keberanian, dan terperangkap dalam mentalitas “jam lima sore”.
Untuk mewujudkan visi pendidikan tinggi yang berdaya saing, Prof. Brian Yuliarto menggarisbawahi perlunya mengatasi tantangan sistemik melalui solusi struktural. Pertama, sistem insentif di kampus harus dirombak. Dosen perlu dinilai berdasarkan dampak nyata penelitiannya, bukan semata-mata jumlah publikasi atau indeks kutipan. Model seperti Fraunhofer Society di Jerman, yang mengelola jaringan penelitian terapan langsung terhubung dengan industri, patut diadopsi. Di sana, dosen didorong untuk menghasilkan paten dan produk yang marketable.
Kedua, peran Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Pusat Penelitian harus didefinisikan ulang sebagai “panglima perang” di medan industri. Mereka harus dibekali kemampuan negosiasi, pemahaman pasar, dan keahlian membangun jaringan strategis, mengingat budaya akademik yang cenderung introvert dan terpaku pada rutinitas kampus.
Ketiga, mahasiswa perlu dididik untuk menjadi agen perubahan, bukan sekadar pengejar nilai. Kurikulum harus diarahkan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kewirausahaan. Program magang di industri, proyek riset kolaboratif, dan inkubator startup di kampus dapat menjadi langkah awal yang signifikan.
Kemajuan bangsa, kata Prof. Brian, bukanlah hadiah yang datang begitu saja, melainkan buah dari kerja keras, ambisi, dan keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Mentalitas “jam lima sore” mungkin terasa nyaman, namun itu adalah jalan yang buntu. Sebaliknya, jalan “jam sembilan malam” penuh tantangan, namun di ujungnya terbentang tujuan besar: bangsa yang inovatif, industri yang kuat, dan ekonomi yang tangguh.
“Sebagai dosen, harusnya merenung: apa peran saya dalam ekosistem ini? Apakah saya cukup 'gila' untuk mendorong mahasiswa keluar dari zona nyaman mereka? Apakah riset saya relevan dengan kebutuhan masyarakat?” serunya. Ia mengajak kita untuk bertanya, “Dan sebagai bangsa, kita perlu bertanya: apakah kita siap mengorbankan kenyamanan demi ambisi?”
Mengutip Thomas Edison, “Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration.” Prof. Brian Yuliarto mengingatkan bahwa kemajuan tidak datang dari mimpi, melainkan dari keringat dan kegigihan. Untuk mewujudkan visi besar ini, diperlukan langkah kolektif: dosen harus berinovasi, mahasiswa harus bermimpi besar, dan kampus harus menjadi jembatan menuju dunia nyata.
Pemerintah pun diharapkan berperan dengan menciptakan kebijakan yang mendukung kolaborasi kampus-industri, seperti insentif pajak bagi perusahaan yang mendanai riset universitas. Pernyataan Prof. Brian Yuliarto ini bukan sekadar kritik, melainkan sebuah seruan untuk bergerak. Ia mengajak kita beralih dari mentalitas “jam lima sore” menuju semangat “jam sembilan malam”, semangat yang telah membawa Korea Selatan dan banyak negara maju lainnya ke puncak inovasi.
Pertanyaannya kini sederhana: maukah kita mengambil jalan terjal itu, atau akan terus berjalan santai dalam kenyamanan yang pada akhirnya hanya membawa pada stagnasi? (PERS)