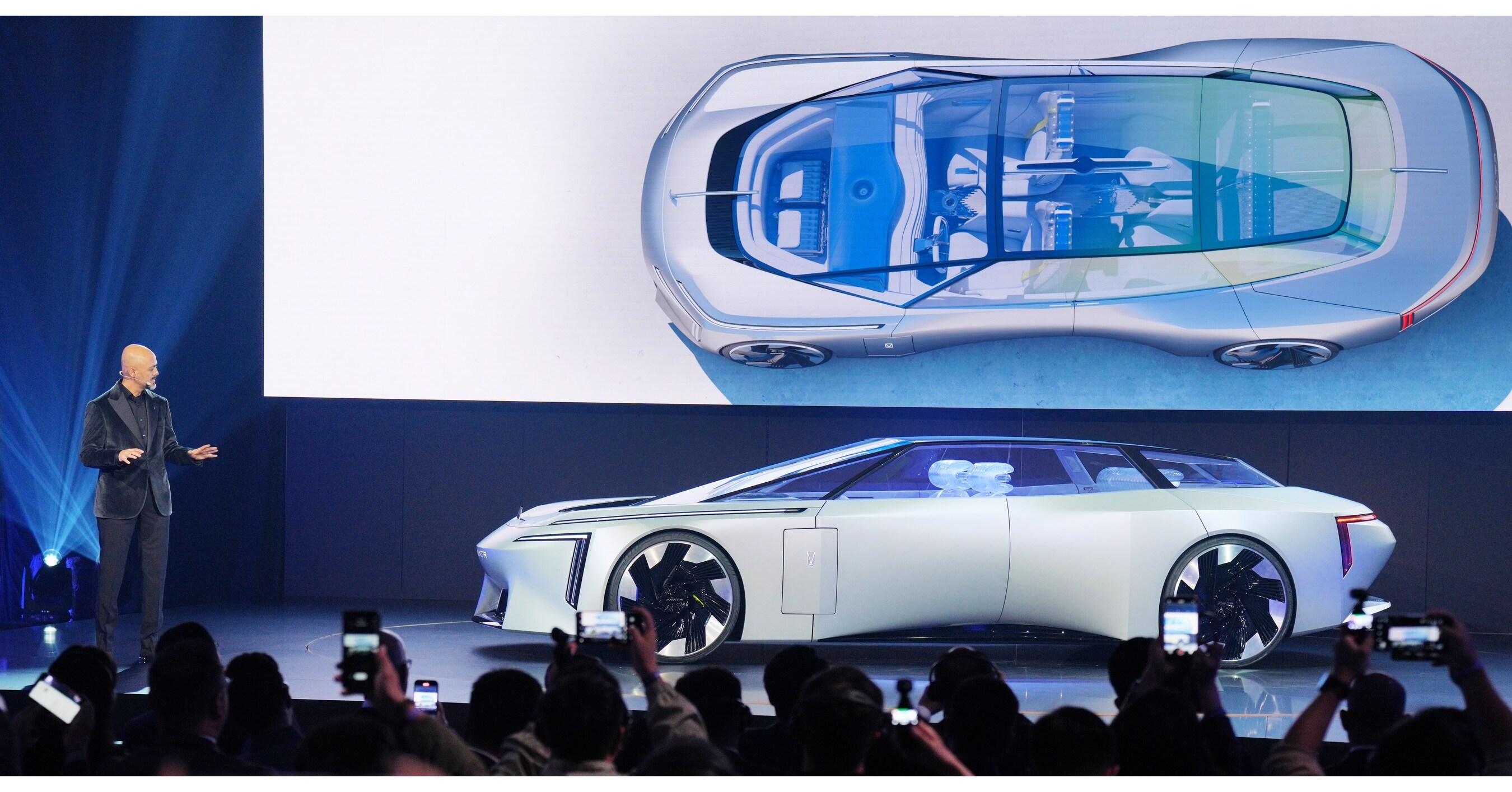OPINI - Pagi itu, deru mesin dan suara sekop terdengar di pinggir sawah tanda dimulainya proyek irigasi yang diharapkan mampu menghidupkan kembali lahan-lahan pertanian warga. Namun, seiring waktu, suara itu perlahan menghilang. Pembangunan berhenti tanpa kejelasan, sementara papan informasi proyek yang dulu berdiri tegak kini mulai pudar tertutup debu. Warga mulai bertanya: ke mana perginya dana pembangunan yang begitu besar nilainya?
Kisah seperti ini bukan hal baru di banyak wilayah pedesaan. Di tengah semangat pembangunan yang digembar-gemborkan atas nama otonomi desa, muncul sisi gelap kekuasaan: penyalahgunaan wewenang dan minimnya transparansi dalam pengelolaan dana publik. Dana yang seharusnya mengalir untuk menghidupi sawah, justru tersendat di tangan mereka yang lebih sibuk menghitung keuntungan pribadi. Kuasa yang seharusnya menjadi alat pelayanan, berubah menjadi alat penguasaan.
🗣️“Korupsi bukan hanya tentang uang yang hilang, tapi tentang kepercayaan publik yang terkikis.”
Fenomena ini memperlihatkan wajah korupsi yang tak lagi identik dengan gedung tinggi di ibu kota. Ia kini menjelma di balai desa, di meja rapat kecil, bahkan diantara tumpukan berkas laporan keuangan yang tak pernah dipublikasikan. Kepala desa yang seharusnya menjadi simbol integritas, justru sering memanfaatkan celah lemahnya pengawasan untuk menyelewengkan dana pembangunan, termasuk proyek vital seperti irigasi perairan sawah.
Dari perspektif hukum administrasi negara, tindakan semacam ini jelas melanggar asas good governance transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Kepala desa adalah pejabat publik dengan public trust obligation kewajiban moral dan hukum untuk mengelola dana rakyat secara terbuka dan bertanggung jawab. Saat prinsip ini diabaikan, yang rusak bukan hanya keuangan desa, melainkan kepercayaan sosial yang menjadi pondasi pemerintahan lokal.
Namun, penyelesaian masalah ini tidak cukup dengan menjerat pelaku korupsi secara pidana. Akar persoalannya jauh lebih dalam: budaya politik lokal yang masih feodal, sistem pengawasan yang lemah, dan kesadaran hukum masyarakat yang rendah. Banyak warga desa masih memandang kepala desa sebagai “penguasa”, bukan “pelayan publik.” Dalam kondisi ini, kritik dianggap ancaman, dan diam menjadi kebiasaan yang aman.
Reformasi dari Akar Rumput untuk keluar dari lingkaran setan ini, diperlukan langkah strategis dan berkelanjutan:
1. Pendidikan hukum bagi masyarakat desa. Warga harus tahu bahwa mereka berhak menuntut transparansi dan mengawasi laporan keuangan desa.
2. Digitalisasi sistem keuangan desa. Semua laporan penggunaan dana desa harus terbuka secara daring agar bisa diakses siapa pun. Transparansi adalah musuh utama korupsi.
3. Pengawasan partisipatif berbasis komunitas. Tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok tani harus dilibatkan sebagai pengawas independen. Pengawasan dari bawah lebih efektif daripada sekadar kontrol birokratis dari atas.
Refleksi: Sekop dan Nurani
Membangun hukum bukan sekadar menegakkan pasal, tetapi menanamkan kesadaran. Desa yang kuat adalah desa yang berani jujur; desa yang berdaya adalah desa yang tak takut bertanya. Ketika hukum hidup dalam kesadaran warga, maka tidak ada ruang bagi kuasa untuk disalahgunakan.
Pada akhirnya, sekop yang menggali tanah seharusnya menggali kesejahteraan, bukan menggali kubur bagi integritas. Kuasa di ujung sekop desa menjadi simbol bagaimana kekuasaan kecil pun bisa menciptakan dampak besar baik untuk kemajuan, maupun untuk kehancuran moral.
Tugas kita sebagai generasi muda hukum bukan hanya memahami aturan, tetapi memastikan aturan itu hidup di tengah masyarakat. Sebab hukum yang hanya tertulis tanpa keberanian untuk ditegakkan, hanyalah tinta tanpa makna.
Judul Opini: Kuasa di Ujung Sekop Desa
(Ketika pembangunan menjadi alat kuasa, bukan kesejahteraan)
Oleh: Wulan Febriyanti
Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Hukum
Universitas Harapan Bangsa (UHB) Purwokerto
Hari/Tanggal: Senin (06/10/2025)