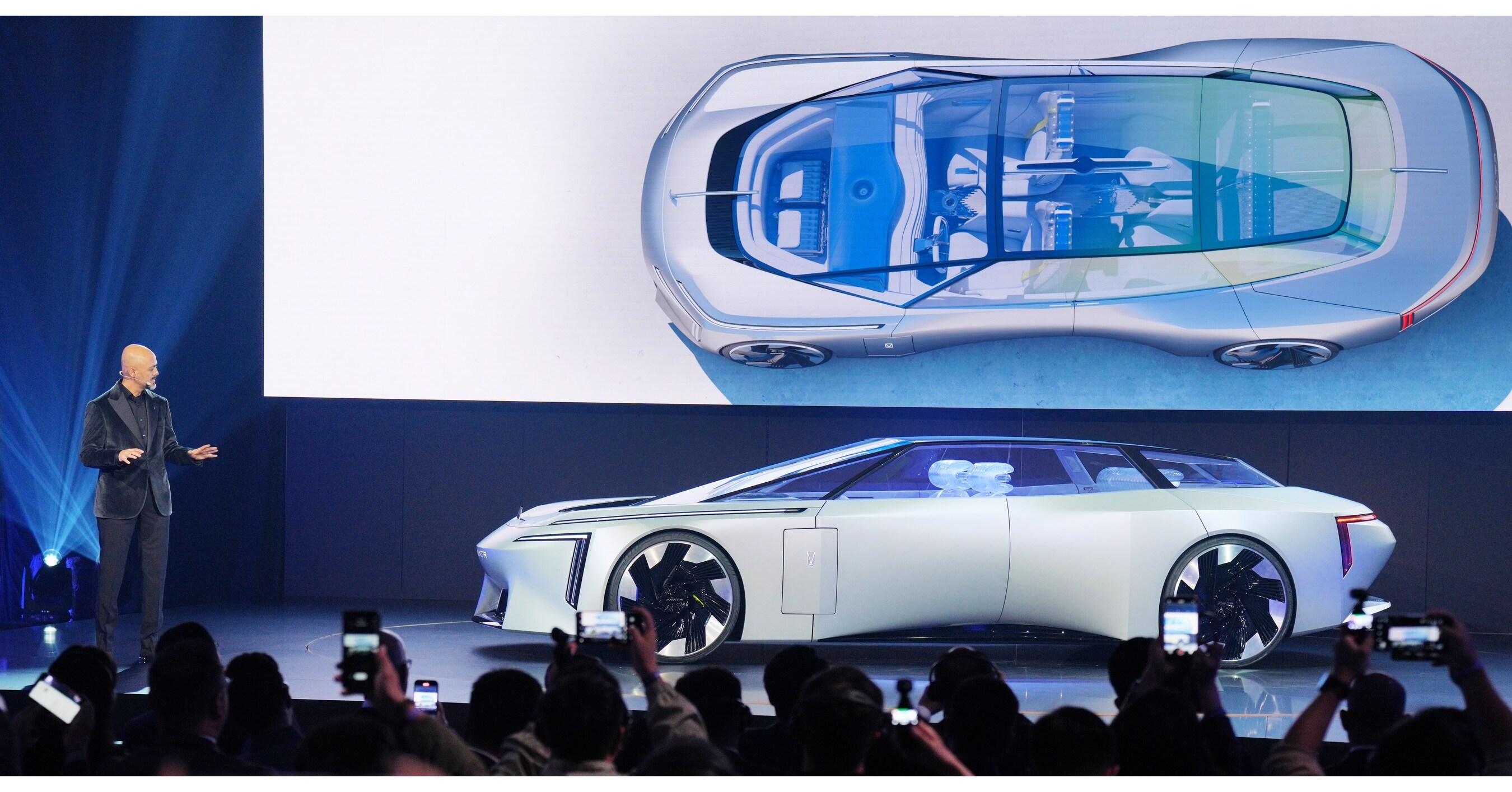Oleh: Indra Gusnady
Di atas kertas, angka-angka itu tampak luhur. Infrastruktur minimal 40 persen, pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen, dan belanja pegawai tak lebih dari 30 persen. Deret angka yang dirancang untuk menjamin rakyat punya jalan yang baik, sekolah yang manusiawi, dan layanan kesehatan yang layak.
Namun di ruang-ruang rapat TAPD di daerah, angka-angka itu kerap berubah menjadi belenggu. Terutama setelah pemerintah pusat mengurangi "Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)" — dua sumber utama pembangunan daerah. Ironisnya, beban baru justru ditambah: 'gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)' kini harus ditanggung dari APBD. Karena di Tahun Anggaran 2026 tidak ada lagi alokasi transfer dana pusat (DAU SG) untuk P3K.
Akibatnya, banyak daerah berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, harus memenuhi ketentuan 'mandatory spending'. Di sisi lain, ruang fiskal terus menyempit. Di banyak kabupaten/Kota, belanja pegawai menembus diatas 40 persen, memaksa mereka memangkas anggaran infrastruktur dan layanan publik. Apa yang semula dimaksudkan untuk memperkuat pembangunan, justru berpotensi melemahkan daya gerak daerah.
𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑘𝑠 𝐾𝑒𝑝𝑎𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛
Dari perspektif akademik, mandatory spending memunculkan paradoks klasik: kepatuhan tanpa keadilan. Daerah dipaksa memenuhi batas minimal pengeluaran tertentu, tapi sumber daya yang disediakan tak selalu memadai. Dalam teori ekonomi publik, ini disebut 'unfunded mandate' — kewajiban tanpa dukungan pembiayaan.
Kajian LPEM UI tahun 2024 menunjukkan hanya empat dari sepuluh pemerintah daerah yang benar-benar bisa memenuhi seluruh kewajiban mandatory spending tanpa defisit. Selebihnya harus memangkas program lain, menunda proyek infrastruktur, atau mengurangi layanan dasar. Kepatuhan pun berubah menjadi formalitas.
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝐿𝑎𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
Efeknya terasa nyata di daerah. Pemangkasan DAK Fisik dan DAU SG (yang ditentukan penggunaannya) membuat banyak proyek jalan berhenti di tengah jalan. Sekolah yang bocor tak kunjung direnovasi karena dana tersedot untuk gaji. Belanja pendidikan tetap tercatat 20 persen, namun sebagian besar habis untuk gaji /tunjangan Guru, honor dan operasional pendidikan.
Di sektor kesehatan, kondisi serupa terjadi. Amanat 10 persen untuk kesehatan sering kali berhenti di laporan, bukan pada layanan. Banyak daerah kesulitan memperkuat puskesmas, layanan gizi, dan penanganan stunting. Semua karena ruang fiskal makin sempit.
Inilah wajah nyata 'krisis fiskal laten daerah' — kondisi ketika kewajiban terus bertambah, tapi kemampuan membiayai semakin terbatas. Mandatory spending berubah dari alat pemerataan menjadi sumber tekanan baru.
𝑀𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑒𝑏𝑖ℎ 𝐷𝑎𝑙𝑎𝑚
Masalah utamanya bukan pada niat kebijakan, melainkan pada desain hubungan fiskal yang masih sentralistis. Pemerintah pusat menetapkan batasan angka tanpa memberi ruang fleksibilitas. Ketika terjadi efisiensi nasional, dana transfer dipangkas sepihak tanpa menyesuaikan beban wajib daerah.
Akibatnya, kepala daerah dihadapkan pada dua pilihan sulit: patuh pada aturan dengan mengorbankan pelayanan, atau menjaga pelayanan dengan risiko administratif. Banyak yang akhirnya memilih “aman secara dokumen”, tapi tak berdaya dalam pelayanan.
𝑀𝑒𝑛𝑎𝑡𝑎 𝑈𝑙𝑎𝑛𝑔 𝐾𝑒𝑎𝑑𝑖𝑙𝑎𝑛 𝐹𝑖𝑠𝑘𝑎𝑙
Kini saatnya meninjau ulang. Jika pusat mengamanatkan 40 persen infrastruktur, 20 persen pendidikan, 10 persen kesehatan, dan 30 persen untuk belanja pegawai, maka desain pembiayaannya juga harus realistis. Pembagian beban gaji P3K perlu dikaji ulang. Dana transfer harus dirumuskan kembali agar selaras dengan kemampuan daerah.
Selain itu, penilaian kinerja anggaran seharusnya beralih dari sekadar angka persentase menuju 'outcome-based budgeting': apakah kualitas pendidikan meningkat? Apakah jalan yang dibangun benar-benar menggerakkan ekonomi lokal? Apakah layanan kesehatan lebih mudah diakses masyarakat?
𝐀𝐤𝐡𝐢𝐫𝐧𝐲𝐚, 𝐒𝐨𝐚𝐥 𝐀𝐦𝐚𝐧𝐚𝐡 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐤
Pertanyaan yang lebih dalam kini muncul: dengan segala keterbatasan itu, bagaimana kepala/Wakil Kepala Daerah bisa menjalankan visi, misi, dan janji politiknya kepada rakyat?
Di tengah tekanan fiskal, janji kampanye tentang jalan mulus, sekolah gratis, perbaikan infrastruktur, peningkatan fasilitas ekonomi dan UMKM, serta Digitalisasi, 'smart Service', sering kali harus berhadapan dengan realitas neraca yang kering. Bila tak ada keberanian merombak kebijakan fiskal antara pusat dan daerah, maka kepala daerah hanya akan menjadi pelaksana angka, bukan pemimpin perubahan.
Angka-angka dalam anggaran memang penting, tapi yang lebih penting adalah ruh di baliknya: kesejahteraan rakyat. Dan di situlah, seharusnya semua kebijakan fiskal berpulang.